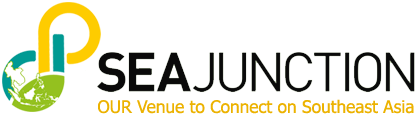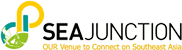Beberapa dinas pendidikan di berbagai distrik di Amerika mengkaji ulang dan melarang sejumlah buku dari perpustakaan sekolah, terutama buku tentang LGBTQ dan kelompok minoritas. Banyak ilmuwan, terutama yang berasal dari Indonesia dan pernah mengalami hal yang sama di tanah air, menyesalkan hal ini.
Sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia ketika ratusan buku yang dinilai meresahkan dan dapat memicu instabilitas, mengandung pemahaman tertentu atau ditulis oleh lawan politik, dirazia, disita dan dilarang beredar.
Di era Orde Lama, yang disasar adalah buku karya penulis atau sastrawan yang dinilai sebagai “kaki tangan imperialis.” Di era Orde Baru, buku-buku yang dinilai berafiliasi dengan kelompok kiri dan mengandung ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme, tidak hanya dilarang beredar, tetapi juga dibakar. Mereka yang membawa buku “terlarang” bahkan diancam bui. Di era reformasi, sebagian buku-buku yang dinilai “kiri” ini masih dilarang, meski tidak sebanyak di era sebelumnya; tetapi ada pula buku terkait orientasi seks dan kelompok minoritas.
Tahukah Anda jika larangan buku serupa juga ada di Amerika?
Sejumlah dinas pendidikan dari Pennsylvania hingga Wyoming dilaporkan tunduk pada tekanan kelompok-kelompok konservatif untuk mengkaji ulang dan kemudian melarang sejumlah buku di perpustakaan sekolah publik.
Direktur American Library Association ALA Deborah Caldwell-Stone awal Januari ini menyampaikan kekhawatirannya pada Axios. “Saya sudah bekerja di kantor ini selama 20 tahun, dan kami belum pernah mengalami tantangan (untuk mengkaji ulang dan melarang buku.red) sebanyak ini dalam waktu sesingkat ini,” ujarnya.

Perpustakaan Sekolah di Spotsylvania County, AS. (Twitter/FreedomMiddleSchool)
The Spotsylvania County School Board di Virginia misalnya, November lalu memerintahkan staf mereka untuk menarik buku-buku “eksplisit secara seksual” dari perpustakaan setelah ada keberatan dari orang tua tentang tema-tema LGBTQ.
Axios juga melaporkan bagaimana The Goddard School District di Kansas menuntut penarikan 29 buku, termasuk “The Handmaid’s Tale” oleh Margaret Atwood dan “The Bluest Eye” oleh pemenang Nobel, Toni Morrison.
The Washington County School District di Utah pada Desember lalu juga memutuskan untuk melarang buku “The Hate U Give” karya Angie Thomas dan “Out of Darkness” karya Ashley Hope Perez, dua buku yang membahas soal rasisme.
Ashley Hope Perez, yang juga mantan guru, lewat Twitter mendorong untuk menggemakan suara siswa yang paling terdampak dengan gelombang pelarangan buku yang bermotif politik.
Ratusan Buku Jadi Target
The American Library Association ALA mengatakan antara bulan September hingga November 2021 saja ada 330 keberatan diajukan terhadap sejumlah buku. Pada tahun 2020, di tengah pandemi dan pembelajaran secara virtual, ada 156 keberatan diajukan terhadap buku dan bahan-bahan di perpustakaan, sekolah dan universitas; yang menarget 273 buku.
Pada tahun 2019, ada 377 keberatan yang menarget 566 buku. Di antara buku-buku yang dilarang itu adalah “George” karya Alex Gino yang mengisahkan tentang seorang gadis transgender, “Stamped : Racism, Antiracism and You” karya Jason Reynolds dan Ibram X. Kendi.
George M. Johnson, penulis “All Boys Aren’t Blue” mengungkapkan bagaimana buku tentang remaja kulit hitam yang menghadapi perkosaan dan incest yang ditulisnya, dilarang di 15 negara bagian, tetapi dicetak ulang delapan kali.
ALA mengkategorikan sebuah buku “dilarang” ketika sekolah atau perpustakaan menariknya dari peredaran, atau ketika sebuah distrik melarang buku tersebut dari mata pelajaran di sekolah.
Relasi Kuasa
Kandidat doktor di State University of New York di Buffalo, Yuyun Sri Wahyuningsih, mengatakan kebijakan mengkaji ulang hingga melarang buku ini terkait dengan relasi kuasa.

Yuyun Sri Wahyuni, kandidat doktor kajian gender di State University of New York di Buffalo. (Foto: pribadi)
“Ini terkait dengan kelompok mana yang sedang berkuasa dan nilai-nilai yang dianggap bertolakbelakang atau asing dan membahayakan dengan yang diyakini oleh kelompok yang berkuasa ini. Buku sebagai karya pemikiran juga dianggap membahayakan karena ada kekhawatiran bergantinya kekuasaan yang mungkin akan mendukung atau membahayakan suatu nilai,” jelasnya.
“Mengapa di Amerika juga terdampak hal ini, menurut saya ini karena menguatnya pandangan konservatif seiring dengan menguatnya gerakan populis di Amerika. Beberapa pakar mengatakan ini akan terus berkembang dan semakin menguat. Ini sangat memprihatinkan karena membuat orang terutama anak-anak, jadi tidak dirangsang untuk berpikir kritis,” imbuh Yuyun.
Bagaimana dengan Indonesia?
Pendiri dan sekaligus Direktur Eksekutif South East Asia Junction di Bangkok, Thailand, Dr. Lia Sciortino mengingat pelarang buku serupa yang pernah terjadi di Indonesia, mulai dari larangan beredar tetralogi Buru: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca karya Pramoedya Ananta Toer, hingga buku yang dinilai dapat memicu keresahan seperti dalam isu Papua.
“Setiap individu selayaknya punya hak yang sama dan setiap orang, tidak penting apakah gender, minoritas, etnis dan lain-lain, punya hak yang sama sesuai konstitusi dan seharusnya dilindungi haknya. Tidak boleh ditabukan. Harus dihormati sama dengan orang lain. Lagi pula mengapa harus dijadikan tabu karena toh meski di sekolah tidak diajar atau di perpustakaan tidak ada, mereka bisa dapat dari tempat lain, ada sosial media yang sangat terbuka,” terangnya.

Dr. Lia Sciortino, pendiri dan Direktur Eksekutif SEA Junction di Bangkok-Thailand.(Foto: pribadi)
“Jadi tidak ada gunanya menutup-nutupi hal seperti kesehatan reproduksi atau kelompok etnis minoritas dan keyakinan tertentu. Di Indonesia dulu ada topik-topik yang tabu, tidak boleh dibicarakan, khususnya yang terkait agama atau etnis. (04’58) Apakah berguna tidak membicarakan hal ini hanya supaya tidak terjadi konflik? Menurut saya tidak! Jika kita menginginkan masyarakat yang inklusif, di mana tidak ada konflik, justru masalah interfaith, hubungan antar kelompok berbeda harus dibicarakan,” lanjut Lia.
SEA Junction yang dikomandoi Lia Sciortino adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang bekerja keras untuk menumbuhkan pemahaman dan apresiasi pada Asia Tenggara dalam semua dimensi sosial budaya, mulai dari seni dan kerajinan hingga ekonomi dan pembangunan dengan meningkatkan akses publik ke sumber pengetahuan.
Lia Sciortino: “Jangan Sampai Orang Cari Informasi dari Sumber Tak Akurat”
Lebih jauh Lia mengatakan pelarangan buku justru membuat orang mencari informasi dari tempat lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.
“Pasti ada perlawanan karena ada diskursus, masyarakat tidak homogen. Selalu ada berbagai pandangan tentang apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang sebaiknya dll. Tapi kita tidak boleh lupa Indonesia juga setuju dengan SDG dan jelas ada prinsip “leave no one behind.” Berarti ini termasuk kelompok minoritas,” tandasnya.
“Tapi pandangan masyarakat pasti ada yang pro dan kontra, ini tidak apa-apa, ini sehat, selama kita bisa diskusi terbuka. Yang mesti diingat, jika terus menerus ditutupi-tutupi dan orang mencari informasi dari tempat lain, maka bisa jadi mereka tidak mendapatkan informasi yang didasarkan pada kajian, atau bukti ilmiah, atau studi. Kita justru harusnya terbuka untuk berdebat sehingga bisa menemukan solusi untuk hidup bersama dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika toh,” imbuh Lia.
American Library Association ALA pada 23 Januari lalu menyampaikan terima kasih atas semua dukungan dalam perjuangan melawan pelarangan buku. [em/jm]
Source: https://www.voaindonesia.com/a/larangan-buku-di-as-cermin-paranoia-/6413590.html